Eksistensi dan Peran
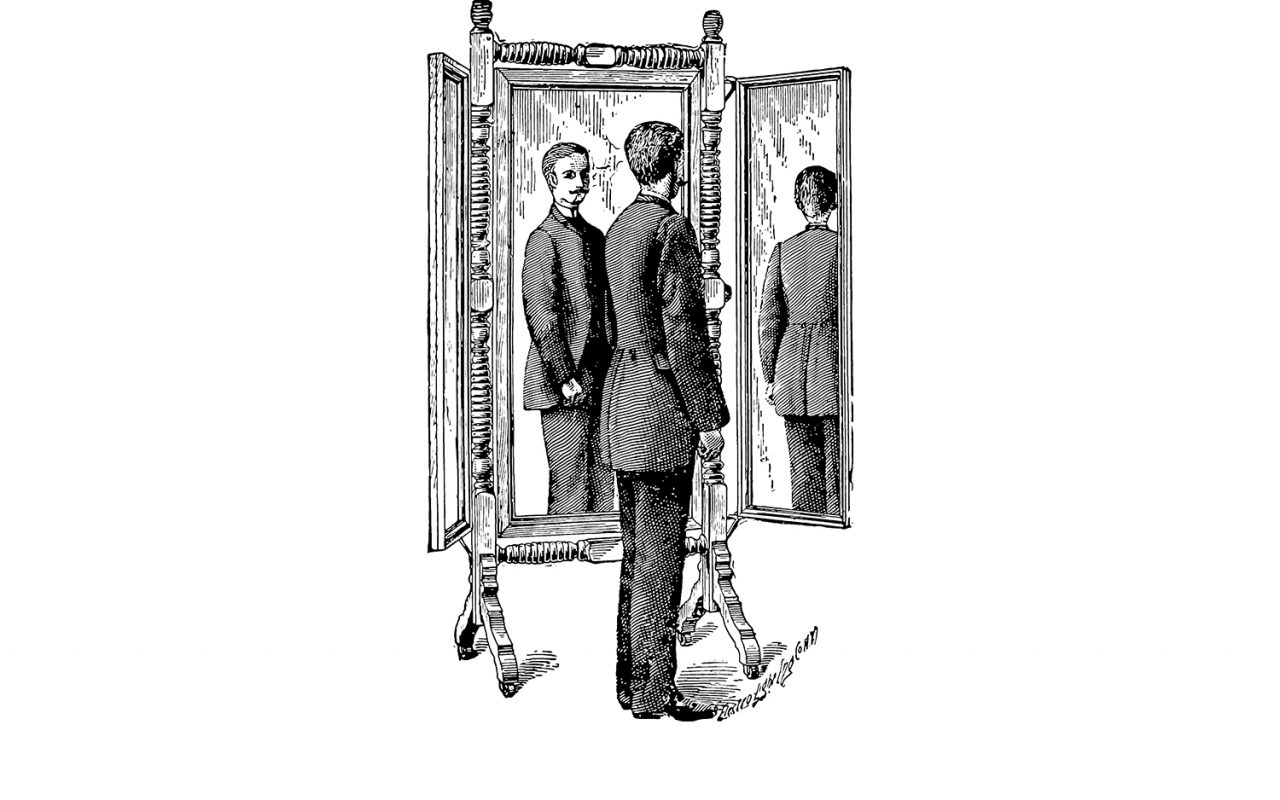
“Man is nothing else but that which he makes of himself”
– Jean-Paul Sartre
Siang itu, usai mengikuti kelas daring Pengantar Ekonometrika, tanpa basa-basi, saya memutuskan untuk langsung melompat ke atas kasur, lalu berbaring sembari memutar acak lagu dari playlist yang telah saya susun pada beberapa waktu yang lalu. Saat itu, algoritma spotify ternyata memutuskan untuk memutar lagu “Kebyar Kebyar” yang dinyanyikan oleh Gombloh. Namun, karena saya sedang tidak ingin membakar jiwa nasionalis saya hingga berapi-api dan menggebu-gebu - seperti saat menonton pertandingan sepak bola Indonesia versus Malaysia di partai final piala AFF. Saya pun mulai menekan tombol next hingga beberapa kali, sampai kemudian, jari saya berhenti pada lagu “Panggung Sandiwara” yang dinyanyikan oleh Nicky Astria.
Saya memutuskan untuk berhenti menekan tombol next pada lagu tersebut karena saya merasa tidak pernah memasukannya ke dalam playlist yang sedang saya putar. Akhirnya, berkat rasa penasaran, saya pun mulai mendengarkannya. Namun, baru saja mendengarkannya dalam beberapa detik, tiba-tiba, saya malah diingatkan akan serangkaian instagram story yang diunggah oleh teman saya pada beberapa waktu yang lalu.
Di instagram story tersebut, teman saya menjelaskan mengenai hubungan eksistensialisme yang diangkat oleh seorang filsuf kontemporer asal Perancis, Jean-Paul Sartre dengan perbuatan perundungan atau bullying. Tetapi, lagu tersebut bukan mengingatkan saya terhadap hubungan eksistensialisme dengan perbuatan perundungan seperti yang dijelaskan oleh teman saya, melainkan membuat saya penasaran mengenai bagaimana hubungan konsep eksistensialisme dengan kata ‘peran’ yang disebut dalam lagu “Panggung Sandiwara”.
“Setiap kita dapat satu peranan,
Yang harus kita mainkan,
Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura”
Eksistensi Mendahului Esensi
Dalam bukunya yang berjudul Being and Nothingness, Sartre menyebutkan bahwa ada dua cara bagi sesuatu untuk berada (etre), yaitu berada pada dirinya (l’etre-ensoi) dan berada untuk dirinya (l’etre-pour-soi).
Berada pada dirinya (l’etre-ensoi) berarti ada dengan tidak berkesadaran, berada yang tidak aktif, namun tidak juga pasif, dan keberadaan sesuatu ini tidak pernah dapat dipisahkan dari dirinya sendiri, serta tidak ada alasan apa pun bagi keberadaannya.
Oleh karena itu, cara berada ini disebut sebagai “ada dalam dirinya sendiri”. Cara berada ini hanya berlaku untuk hal-hal selain manusia, seperti benda-benda, hewan, atau tumbuhan. Semua benda-benda ada dalam dirinya sendiri, tidak memiliki alasan mengapa mereka demikian, dan bahwa dia adalah dia (being it is what it is). Kalau pun sesuatu ini memiliki perkembangan, perkembangannya pun kaku, karena disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, seperti benih yang pasti tumbuh menjadi pohon.
Perkembangan ini, menurut Sartre merupakan sesuatu yang memuakan, yang ada begitu saja, tanpa kesadaran, tanpa makna. Oleh karena itu, menurutnya, sesuatu yang berada pada dirinya sendiri (l’etre-ensoi) ini tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kenyataan bahwa dirinya adalah sesuatu dengan bentuk yang sedemikian rupa.
Namun, manusia tidaklah demikian, cara berada manusia adalah berada untuk dirinya (l’etre-pour-soi), yaitu berada dengan sadar akan dirinya. Manusia sebagai sosok yang berada untuk dirinya berbeda dengan benda, sebab benda hanyalah benda, sedangkan manusia memiliki kesadaran dan kebebasan untuk membentuk dirinya dengan kemauan dan tindakannya.
Dengan demikian, Sartre berpendapat bahwa konsep eksistensi pada manusia adalah l’existence précède l’essence, yang berarti eksistensi manusia justru mendahului esensinya, tidak seperti benda yang merupakan sebaliknya.
Agar lebih mudah dipahami, dalam penjelasannya, Sartre menggunakan contoh sebuah pisau pemotong kertas. Sebelum pisau pemotong kertas dibuat, konsep mengenai pisau pemotong kertas sudah ada terlebih dahulu, yaitu “alat untuk memotong kertas”. Sehingga, sampai kapanpun pisau pemotong kertas tersebut tidak akan dapat mengubah esensinya, karena esensi dari pisau pemotong kertas tersebut mendahului eksistensinya.
Eksistensi yang dimaksud di sini adalah tampak, terjadi dalam ruang dan waktu, dan menekankan jawaban dari pertanyaan “apakah sesuatu itu ada?”. Selain itu, eksistensi di sini juga bukan sekadar ada atau berada, melainkan mempunyai arti yang lebih khusus, yaitu cara sesuatu berada di dalam dunia, dan cara berada manusia berbeda dengan benda-benda.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Eksistensialisme, Søren Kierkegaard (dalam Yussafina, 2015: 42–43), bahwa eksistensi manusia bukanlah “ada” yang statis, melainkan “ada” yang “menjadi”. Proses “menjadi” ini adalah perubahan yang bebas, karena manusia memiliki kebebasan untuk memilih, dan adanya kebebasan tersebut menuntut manusia mempertanggungjawabkan perbuatan yang didasari atas kebebasan tersebut.
Sedangkan esensi di sini adalah sesuatu yang tidak tampak atau hakikat dari sesuatu, yang membedakan corak suatu benda dengan corak benda-benda lainnya, dan lebih menekankan terhadap jawaban dari pertanyaan “apakah itu?”.
Maka, ketika seseorang sudah memahami konsep esensi akan sesuatu, orang tersebut sudah dapat memikirkan benda tersebut tanpa harus memedulikan keberadaan benda tersebut, seperti halnya mesin waktu. Ketika seseorang sudah mengetahui konsep esensi dari mesin waktu — yaitu mesin yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan antar waktu. Maka, orang tersebut sudah dapat membayangkan mesin waktu tanpa harus memedulikan apakah mesin waktu itu ada atau tidak.
Eksistensi manusia mendahului esensinya, berarti bahwa manusia bukanlah sosok yang sudah diketahui terlebih dahulu esensinya, karena manusia itu bukan sekadar “ada”, seperti benda tidak hidup yang tidak memiliki kesadaran, kebebasan, tanggungjawab, serta kemampuan untuk berkembang dan menentukan masa depannya. Tetapi manusia itu adalah sosok yang belum selesai, dalam arti masih harus dibentuk, sehingga manusia harus berproses “menjadi” terlebih dahulu untuk bisa diketahui esensinya.
Proses “menjadi” ini merupakan sekumpulan tindakan yang dilakukan manusia, yang berarti manusia sendirilah yang menentukan esensi, nilai, moralnya, serta akan menjadi apa dia. Seperti yang terkandung dalam pernyataan Sartre yang terkenal, “man is nothing else but what he makes of himself”
Dunia Ini Panggung Sandiwara
Lagu “Panggung Sandiwara” yang diciptakan oleh Ian Antono dan Taufik Ismail, mengumpamakan bahwa dunia ini adalah sebuah panggung sandiwara, dan setiap manusia di dalamnya memiliki peran yang harus dimainkan.
Selanjutnya, jika ditelusuri lebih jauh, frasa “Dunia ini Panggung Sandiwara” pertama kali dipopulerkan oleh seorang pujangga legendaris asal Inggris, William Shakespeare dalam karyanya yang berjudul As You Like It.
Dalam karya tersebut, Shakespeare menulis sebuah monolog yang menceritakan bahwa dunia adalah panggung sandiwara, dan manusia merupakan pemeran di dalamnya yang memiliki waktu tersendiri kapan baginya untuk naik ke atas panggung dan turun dari panggung.
All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first, the infant,
Mewling and puking in the nurse’s arms.
Then the whining schoolboy, with his satchel
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress’ eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths and bearded like the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the cannon’s mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lined,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slippered pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side;
His youthful hose, well saved, a world too wide
For his shrunk shank, and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.
Dalam monolog tersebut, Shakespeare menjelaskan bahwa sandiwara manusia di dunia dibagi menjadi tujuh babak yang masing-masing merepresentasikan masa-masa hidup manusia di dunia.
Pertama, sandiwara manusia di dunia diawali sebagai sosok bayi yang lemah dan hanya bergantung kepada pengasuhnya.
Kedua adalah sosok anak sekolah, yaitu sosok yang masih segar dan menggebu-gebu penuh api pemberontakan.
Ketiga adalah sosok pecinta, yaitu masa ketika manusia sedang kasmaran termakan api cinta yang meledak-ledak.
Keempat adalah sosok prajurit, yaitu masa ketika manusia sedang dalam pencarian pengakuan atas dirinya, yang panas akan kehormatan dan mengejar reputasi semu.
Kelima adalah sosok hakim, yaitu ketika manusia berada dalam keadaan makmur dan bijaksana, yang dianalogikan oleh Shakespeare sebagai sosok yang memiliki mata berat, berjanggut lebat, dan penuh akan pertimbangan.
Selanjutnya adalah sosok orang tua keriput yang menyisakan kenangan pada masa mudanya dan kembali lemah seperti ketika ia masih seorang bayi, dan terakhir, babak yang mengakhiri rangkaian pertunjukan manusia di dunia, yaitu masa kanak-kanak kedua, tanpa gigi, tanpa mata, tanpa rasa, tanpa semuanya, atau kematian.
Peran dan Eksistensi
Jika dihubungkan dengan eksistensialisme, kata ‘peran’ dapat diartikan sebagai salah satu bentuk bagi manusia dalam menghasilkan esensi, atau usaha manusia dalam proses “menjadi”nya, dan karena kebebasan dan kesadaran yang dimilikinya, manusia bebas untuk menentukan peran apa yang akan dimainkannya, seperti berperan sebagai seorang advokat lingkungan yang menyuarakan bahayanya perubahan iklim, ataupun sebagai seorang buzzer di media sosial yang mengidolakan afiliasi politiknya seperti hooligan Eropa Timur dalam mendukung tim sepak bola kesayangannya.
Pilihan-pilihan tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat diganggu dan ditentukan oleh orang lain, karena eksistensi manusia mendahului esensi, yang berarti manusia memiliki kebebasan untuk menentukan esensi dirinya sendiri.
Namun, menurut Sartre, kebebasan tersebut hanya akan memiliki arti jika manusia itu mampu menentukan pilihan yang terbaik baginya dalam menentukan esensinya, serta mampu bertanggungjawab atas pilihan itu. Selain itu, Sartre juga mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas pilihan tersebut bukan hanya terhadap individu itu sendiri, melainkan mencakup tanggung jawab atas semua manusia.
“…I am responsibe for myself and for everyone
else. I am creating a certain image of man of my
own choosing. In choosing myself, I choose
man”
Pilihan yang diambil manusia merupakan suatu penegasan nilai, dan sejak adanya pertanggungjawaban atas seluruh manusia yang muncul akibat pilihan tersebut, maka, pilihan yang dipilih mestinya selalu merupakan pilihan yang terbaik bagi sesama manusia.
Oleh karena itu, seseorang yang hendak menentukan pilihan, baiknya menanyakan pada dirinya terlebih dahulu, apa yang akan terjadi jika setiap manusia di dunia melakukan apa yang dia lakukan.
Selain itu, kebebasan manusia juga pada kenyataannya tidaklah benar-benar bebas, melainkan bergantung pada eksistensinya. Adapun, eksistensi manusia akan berakhir dengan kematian, sehingga kebebasan manusia tidaklah bersifat mutlak, karena dibatasi dan dihalangi oleh kematian.
Seperti yang dijelaskan Shakespeare, kehidupan manusia di dunia ini diakhiri dengan kematian, yang merupakan babak terakhir dalam sandiwaranya selama di dunia. Pada babak ini, berakhirlah eksistensi dan kebebasan manusia, sehingga yang tersisa hanyalah esensinya yang selama ini mereka bentuk dengan memainkan perannya di dunia.
Selanjutnya, esensi tersebut akan dimaknai dan dikenang oleh orang lain atas kehidupannya, karena dengan esensi ini, orang lain akan dapat membayangkan manusia seperti apa mereka tanpa harus memedulikan keberadaannya di dunia ini, seperti ketika memaknai kehidupan seorang juru damai, Mahatma Gandhi, ataupun seorang kaisar lalim, Caligula.
Kita tidak perlu benar-benar peduli apakah mereka benar-benar pernah ada di dunia ini atau tidak, tetapi yang jelas, kita tetap dapat membayangkan peran apa yang mereka mainkan melalui esensi yang mereka tinggalkan.
Jadi, peran apa yang akan kalian mainkan? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak?, atau peran bercinta bikin orang mabuk kepayang?
Referensi
Yunus, F. M. (2011). Kebebasan Dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre. Jurnal Al-Ulum, Volume. 11, Nomor 2: Hal. 267–282.
Yussafina, D. M. (2015). Eksistensialisme Jean Paul Sartre Dan Relevansinya Dengan Moral Manusia. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
All the world’s a stage. (t.thn.). Diambil kembali dari Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/All_the_world’s_a_stage
Ted Ed. (2019, Februari 2). “All the World’s a Stage” by William Shakespeare. There’s a Poem For That. Diambil kembali dari Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_jaSFtcDEiE
